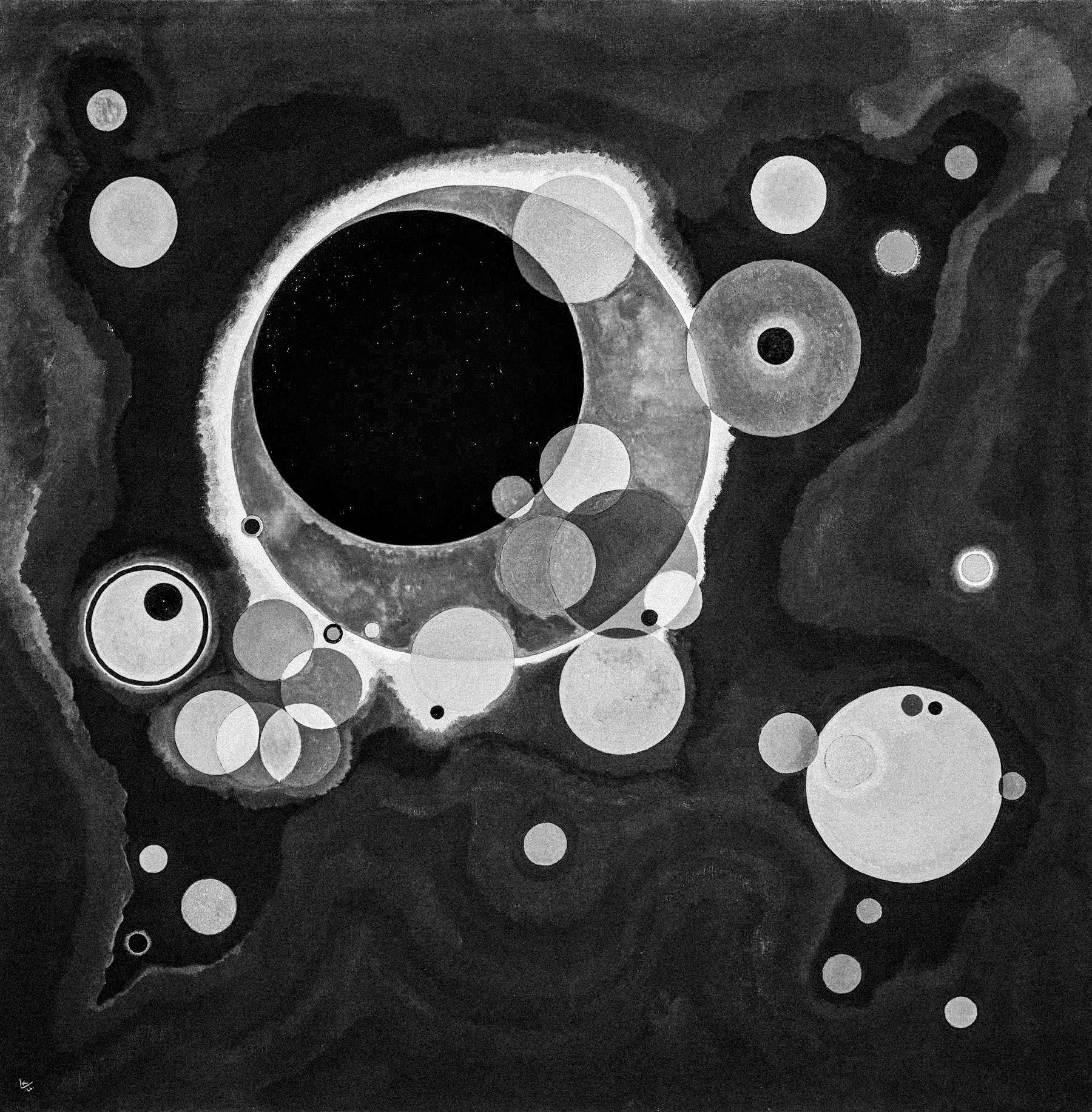“Formulaku
untuk kebesaran dalam diri manusia adalah Amor Fati: bahwa seseorang tak ingin
sesuatu yang berbeda, tak masa depan, tak masa lalu, tak pula semua kekekalan.
Tak hanya menanggung apa pun yang diperlukan—tetapi mencintai semua itu.”
—Nietzsche,
Ecce Homo (1992)
Begitulah,
sabda si Dinamit-Nietzsche di buku otobiografinya, Ecce Homo—sebelum
jatuh ke dalam penyakit kejiwaan pada bulan Januari 1889 dan kemudian, tak
berselang lama dari itu—meninggal pada 25 Agustus 1900 karena pneumonia (infeksi/radang
paru-paru). Meski dikarang pada tahun 1888, namun terbitan pertama buku
tersebut mengudara pada 1908—sekitar 20 tahun setelah bukunya selesai ditulis,
atau 8 tahun pasca Nietzsche wafat.
Lantas
apa yang Nietzsche sebut sebagai formula bernama “Amor Fati” itu? Apakah itu semacam
mantra ajaib penolak bala?
Pendek
kata, Amor Fati adalah sebuah frasa dari bahasa Latin yang jika diterjemahkan
secara kasar berarti: “Mencintai Takdir”. Amor Fati mempunyai bentuk yang lebih
lengkap, puitis, dan monumental: yakni, 'Fatum Brutum Amor Fati'; yang
kira-kira jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti:
“Mencintai takdir walau takdir hadir dengan begitu brutal”. Mengutip dari
merriam-webster.com, Amor Fati (amor fa·ti; ˈä-ˌmȯr-ˈfä-tē) bermakna: mencintai
takdir; menyambut semua pengalaman hidup dengan baik. Jika mengutip dari
urbandictionary.com, Amor Fati memiliki makna: menggambarkan suatu sikap yang
melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup seseorang; cara bersikap pada
segala sesuatu.
Dengan
kata lain, Amor Fati adalah suatu sikap penerimaan yang tegas dan antusias atas
segala sesuatu—berpuncak pada kemampuan memaknai past/present/future
dalam tenses hidup kita—agar kita mampu menjalani hidup dengan energik,
tanpa kecemasan, dan mampu vis a vis menatap mata kematian tanpa satu
pun penyesalan.
Secara
literal, frasa Amor Fati justru bukan ingin menolak bala, tetapi mengajak kita
untuk menerimanya secara brutal. Maka tak heran, frasa ini keluar dari mulut
Nietzsche, sebab ia pernah mengungkapkan bahwa “inti dari realitas adalah
kekacauan, adalah kaotis”—sehingga hal paling waras dan logis yang dapat kita
lakukan, pertama-tama, adalah menerima kehidupan lengkap dengan seluruh keruwetan
problemanya, kebudugan dunianya, dan tentu takdirnya yang sering luar biasa kejamnya.
Sejatinya,
frasa Amor Fati telah hadir jauh sebelum Ecce Homo, misalnya dalam Die
fröhliche Wissenschaft (La Gaya Scienza/The Gay Science/The Joyful
Wisdom/The Joyous Science), Nietzsche menulis:
“Aku
ingin belajar lebih banyak lagi untuk melihat keindahan macam apa yang
diperlukan dalam segala sesuatu; maka aku akan menjadi salah satu dari mereka
yang membuat segala sesuatu menjadi indah. Amor fati: biarkan itu menjadi
cintaku selanjutnya! Aku tak ingin melancarkan perang melawan apa yang jelek.
Aku tak ingin menuduh; aku bahkan tak ingin menuduh mereka yang menuduh.
Memalingkan muka akan menjadi satu-satunya bentuk negasiku. Dan semua dalam
semua dan secara keseluruhan: suatu hari nanti aku hanya ingin menjadi
seseorang yang mengatakan ‘Ya’ pada kehidupan.”
—Nietzsche,
The Joyous Science (2018)
Selain
itu, Amor Fati juga tercatat dalam Der Fall Wagner (termasuk dalam
“Nietzsche Contra Wagner”, sebuah esai kritik Nietzsche terkait pemikirannya
tentang komposer Richard Wagner):
“Amor
fati: adalah inti dari keberadaanku ... Hanya penderitaan besar; penderitaan
besar itu, di mana kita tampaknya berada di atas api kayu hijau, penderitaan
yang memakan waktu—memaksa kita, para filsuf, untuk turun ke kedalaman terdalam
kita, dan melepaskan semua kepercayaan, semua sifat baik, semua pengurangan,
semua kelembutan, semua mediokritas—hal-hal yang sebelumnya kita pertaruhkan di
atas kemanusiaan kita.”
—Nietzsche,
Nietzsche Contra Wagner (2021)
Amor
Fati dan Stoikisme
Berbicara
perihal ‘Amor Fati’, tak komprehensif bila tanpa membahas Stoikisme—sebab Nietzsche,
secara filosofis, sedikit banyak terpengaruh oleh para Stoik. Stoikisme,
singkatnya, adalah sebuah aliran filsafat Yunani Kuno, dan merupakan salah satu
dari tiga mazhab filsafat besar pada periode Helenistik—satu era dengan Epikureanisme
dan Pyrrhonisme—yang didirikan di kota Athena, Yunani, oleh Zeno dari Citium
pada awal abad ke-3 SM.
Dalam
beberapa literatur tentang Zeno kita dapat menemukan pemikirannya yang berwarna
Amor Fati:
“Takdir
adalah rantai sebab-akibat yang tak ada habisnya, di mana segala sesuatunya
ada; alasan atau formula di mana dunia berjalan.”
—Zeno
dari Citium
Dalam
karya-karya Marcus Aurelius, salah satu figur Stoik paling terkenal pun
demikian, misalnya pada Ta eis heauton (Meditations):
“Dia
hanya melakukan apa yang menjadi tugasnya, dan terus-menerus mempertimbangkan
apa yang dunia siapkan untuknya—melakukan yang terbaik, dan percaya bahwa
semuanya adalah yang terbaik. Sebab kita membawa takdir kita bersama kita—dan
takdir itu mengantarkan kita.”
—Aurelius, Meditations (2006)
Figur
intelektual Stoik pun tak luput menyatakan pandangannya yang bernuansa Amor Fati—baik
secara tindakannya yang menerima hukuman bunuh diri yang dijatuhkan kepadanya
maupun dalam karya-karya awalnya seperti Ad Lucilium Epistulae Morales (Letters
from a Stoic):
“Kebahagiaan
sejati adalah memahami kewajiban kita kepada Tuhan dan manusia; untuk menikmati
saat ini, tanpa ketergantungan pada kecemasan akan masa depan; bukan untuk
menghibur diri kita sendiri dengan harapan atau ketakutan, tetapi untuk merasa
puas dengan apa yang kita miliki, yang sangat cukup ini.”
—Seneca,
Letters from a Stoic (2004)
Filsuf
Stoik lain, Epictetus, pun mencetuskan ungkapan yang kurang lebih seperti Amor
Fati dalam bahasa dan terma Stoikisme—dia menulis:
“Jangan
menuntut hal-hal terjadi seperti yang kau inginkan, tetapi berharaplah hal itu
terjadi sebagaimana adanya, dan kau akan berjalan dengan baik.”
—Epictetus,
The Discourses of Epictetus: The Handbook (1995)
Dengan
demikian, besar kemungkinan Amor Fati adalah pola pikir Stoik untuk
memanfaatkan masa kini dan secara total melakukan yang terbaik terlepas dari apa
pun hasilnya dan apa pun yang terjadi: misalnya, perihal bagaimana
memperlakukan setiap momen—tak peduli seberapa sulitnya—sebagai sesuatu yang
harus dihadapi dengan berani, bukan dinegasikan atau dihindari.
Mengapa
Amor Fati?
Kini,
yang menjadi pertanyaan mungkin adalah mengapa kita harus bersusah payah
menggali makna dari frasa Latin di kuburan-pemikiran Nietzsche—yang bahkan
sudah berumur lebih dari 134 tahun itu (dan kuburan-pemikiran para Stoik yang
jauh lebih purba)—untuk kemudian menghayati atau bahkan mengaplikasikannya
dalam hidup kita?
Satu
yang jelas, gagasan-gagasan ketuhanan, ritus-ritus keagamaan, dan ide-ide
seseorang tak akan pernah pernah mati—selama itu tetap relevan dengan kondisi
zaman. Tubuh dapat membusuk dan melebur dengan tanah, tetapi apa yang telah dia
formulasikan—gaungnya masih mungkin terdengar lantang sampai sekarang dan
sampai masa-masa yang akan datang. Secanggih apapun peradaban umat manusia,
pada hakikatnya, tetap saja ada hal-hal yang tak dapat manusia seluruhnya dan
seutuhnya kendalikan. Manusia boleh berbangga, manakala kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi berhasil membawa seekor anjing bernama Laika pergi ke
luar angkasa, mendaratkan Armstrong dan Aldrin di bulan, robot-robot canggih
ciptaan manusia sudah hilir-mudik di wajah planet lain, rencana futuristik
untuk Kolonisasi Mars 2030, dan seterusnya dan seterusnya.
Akan
tetapi, jauh di lubuk hati, pada gilirannya, kita mungkin menyadari sesuatu
bahwa masih banyak hal-hal yang tak mampu kita kendalikan. Katakanlah
waktu—sampai tulisan ini selesai dibuat—belum ada teknologi sesinting-secanggih
mesin waktu yang memungkinkan penggunanya melakukan perjalanan waktu, yang dapat
dikendalikan dengan sesuka pikiran-perasaan penggunanya. Yang menjadi masalah
adalah, manusia itu budak sang waktu, seperti yang telah dipuisikan oleh
Baudelaire, penyair besar Prancis itu dalam Enivrez-vous: “Kau harus
selalu mabuk. Hanya itu satu-satunya—cara yang ada. Agar tak merasakan beban
waktu yang mengerikan, yang mematahkan punggungmu, dan membungkukkanmu ke bumi,
kau harus terus-menerus mabuk.” Hampir setiap orang di muka bumi ini,
rasa-rasanya, memiliki semacam tendensi tinggi untuk mengubah masa lalunya,
atau pergi melihat masa depannya.
Lalu,
apa hubungannya semua ini dengan Nietzsche, Amor Fati, dan Stoikisme?
Amor
Fati adalah kredo untuk menerima, merangkul, dan mencintai segala sesuatu yang
telah terjadi, sedang terjadi, belum terjadi, mungkin terjadi, tak mungkin
terjadi, atau tak akan terjadi—di dimensi ketiga (kenyataan) yang dipenuhi
berbagai kemungkinan-kemungkinan acak dan ensiklopedis. Secara lebih luas,
mengafirmasi dengan tegas dan askenden hal-hal yang tak dapat kita
kendalikan, sekaligus mencintai perubahan-perubahan yang tak terelakkan.
Semacam upaya untuk menjustifikasi sekaligus menjawab aforisme ‘Phanta Rei’ à
la Heraclitus, seorang filsuf pra-socrates, yang menekankan bahwa satu yang
pasti dalam kehidupan adalah perubahan konstan. Secara implisit, kredo ini
seperti mengisyaratkan bahwa sifat alam semesta adalah selalu berubah.
Perubahan adalah sesuatu yang niscaya. Dengan demikian, tanpa perubahan—kita
tak akan ada, kesadaran baru tak akan ada, daya-daya tafsir baru tak akan ada,
kita tak akan tertawa ketika mengingat tragedi, tak akan belajar mencintai
keberadaan dari ketakberadaan, dan tak akan mencipta sesuatu. Tanpa perubahan,
kita tak akan pernah mengalami asam-garam itu semua.
Apakah
perubahan itu baik, buruk, menyenangkan, menyiksa, menggairahkan, atau
merugikan—itu persoalan lain. Miliaran tahun, umat manusia mengalami evolusi,
perubahan, transformasi, mutasi—perkembangan yang eksponensial telah membawa
kemungkinan ke tempat kita berada sekarang. Penulis tak akan dapat menulis
hal-ihwal Amor Fati—jika bukan karena setiap peristiwa yang telah terjadi jauh
sebelum saat ini: misalnya, karena seekor ikan purbakala yang mulai bosan hidup
di dalam air, berpikir untuk naik ke daratan dan menjadi primata—lalu
berevolusi sedemikian rupa, kemudian menjadi cikal bakal Homo Sapiens; atau
dengan pendekatan agama samawi yang ditopang literatur-literatur abrahamik,
karena sepasang manusia bernama Adam dan Hawa memakan buah terlarang, kemudian
ditendang dari surga—lantas melahirkan seluruh keturunan manusia di muka bumi
ini. Dengan membayangkan seperti itu, mungkin kita bisa mulai belajar untuk
mencintai takdir dengan paripurna.
Nietzsche
pun mengadvokasi ini: bahwa kita tak boleh lari dari takdir apalagi bersembunyi
dari takdir. Kita harus menerimanya. Akan tetapi, lebih dari sekadar penerimaan
biasa, lebih-lebih, kita harus mencintai takdir kita dan menerimanya secara
utuh apa adanya. Kita perlu menerimanya, memanfaatkannya, dan menggunakannya
untuk membuat sesuatu yang produktif—sesuatu yang bernilai seni, kreatif, dan
filsafati. Meratapi dengan sesal hal-hal yang telah terjadi, hanyalah
memperpanjang nafas penderitaan yang tak perlu—hanyalah membuang-buang waktu.
Ketika
kita menerima apa yang terjadi pada kita, setelah memahami bahwa hal-hal
tertentu—khususnya hal-hal buruk dan menyebalkan—berada di luar kendali kita
(baca: Dikotomi Kendali-nya Stoikisme) kita hanya akan di hadapkan
dengan ini: mencintai apa pun yang akan terjadi pada kita, menghadapinya dengan
keceriaan di rongga dada, dan dengan energi besar serta meletup-letup, kita
akan terus bersemi, lagi dan lagi. Meskipun dunia memberi winter-yang-menyakitkan,
namun selalu ada summer-yang-tak-terkalahkan di dalam diri kita, meminjam
interteks Camus, seorang eksistensialis yang lebih nyaman disebut absurdis. Selain
itu, bahwa dibutuhkan api yang begitu panas untuk membentuk emas. Terbentur,
terbentur, melebur—jika meminjam ungkapan Tan yang sudah dimodifikasi agar
sesuai dengan konteks ini. Poinnya adalah bahwa selain pilihan, ada
kebolehjadian tinggi bahwa hidup juga merupakan kompromi.
“Dari
sekolah perang dalam kehidupan—apa yang tak membunuhku, membuatku jauh lebih
kuat.” tulis Nietzsche dengan berani tanpa kecondongan masokis. Bukan untuk
mencari pembenaran atas trauma dan luka masa lalu, tetapi lebih menawarkan
semacam antidot-fakta bahwa tak ada kekuatan tanpa penderitaan. Bahwa kebijaksanaan
harganya adalah pedihnya belajar dan istiqomah tingkat tinggi untuk bangkit
dari kebahlulan.
Pada
akhirnya, Amor Fati, adalah perihal bagaimana mengelola energi, emosi, waktu,
dan tenaga kita dengan bijak. Terakhir, takdir mungkin memang piawai bangsatnya
hadir seperti bajingan paling asu, tetapi hanya hidup singkat ini yang
kita punya. Kita tak dapat mengontrol apa-apa yang di luar batas-batas
kebebasan-kekuasaan kita, tetapi kita selalu dapat mengontrol apa yang bisa kita
persepsikan dan mengelola serta mengkalkulasi tindakan macam apa yang dapat
kita lakukan untuk mengubah setiap negatif menjadi positif. Sebab, ketimbang
kalimat pasif, manusia adalah kalimat aktif—yang dengan segala
intelektualitasnya semestinya mampu menjadi ‘aktor’ bukan ‘spektator’ bagi
kehidupannya sendiri. Terdengar cukup eksistensialis, memang.
Que
Será, Será; apapun yang akan terjadi, terjadilah. Jalani,
nikmati, Amor Fati!
Referensi:
Nietzsche,
Friedrich, 1992, Ecce Homo, London: Penguin Classics.
Nietzsche,
Friedrich, 2018, The Joyous Science, London: Penguin Classics.
Nietzsche,
Friedrich, 2021, Nietzsche Contra Wagner, California: Stanford University
Press.
Heraclitus,
2003, Fragments, London: Penguin Classics.
Aurelius,
Marcus, 2006, Meditations, London: Penguin Books.
Seneca,
2004, Letters from a Stoic, London: Penguin Books.
Epictetus,
1995, The Discourses of Epictetus: The Handbook, Fragments, London: Everyman
Paperback.
Tom
Stern, VIII—Nietzsche, Amor Fati and The Gay Science, Proceedings of the
Aristotelian Society, Volume 113, Issue 2_pt_2, 1 July 2013, Pages 145–162,
https://doi.org/10.1111/j.1467-9264.2013.00349.x
Panaïoti,
A. (2012). Amor fati and the affirmation of suffering. In Nietzsche and
Buddhist Philosophy (pp. 91-131). Cambridge: Cambridge University Press.
doi:10.1017/CBO9781139382144.007
Thiele,
Leslie Paul. "TEN. Amor Fati and the Eternal Recurrence". Friedrich
Nietzsche and the Politics of the Soul: A Study of Heroic Individualism,
Princeton: Princeton University Press, 2020, pp. 197-206.
https://doi.org/10.1515/9780691222073-014
Brodsky,
Garry M. (1998). Nietzsche's notion of Amor fati. Continental Philosophy Review
31 (1):35-57.